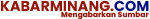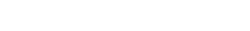“Saya tidak mau banyak keluar rumah. Malu juga. Takut anak dengar omongan orang,” ujarnya.
Marlina mengatakan, kondisi psikologis anaknya yang menjadi korban pencabulan juga belum pulih. Anak itu kini lebih sering menyendiri dan tak lagi seceria dulu.
“Kadang tiba-tiba menangis. Itu yang paling bikin hati saya hancur. Dia yang jadi korban, tapi harus menanggung semuanya,” ucap Marlina dengan suara bergetar.
Ia mengaku masih sulit tidur sejak kejadian. Setiap malam, pikirannya dipenuhi bayangan anaknya yang trauma, dan suaminya yang kini berada di balik jeruji.
“Kadang saya marah sama keadaan. Tapi mau bagaimana lagi. Semua sudah terjadi,” katanya.
Tentang suaminya, perasaannya campur aduk. Ia tahu perbuatan ED salah di mata hukum. Tapi ia juga paham amarah seorang ayah yang mengetahui anaknya disakiti.
“Saya tidak membenarkan. Tapi saya tahu bapaknya sakit hati sekali. Siapa orang tua yang tahan lihat anaknya begitu,” katanya.
Sejak ED ditahan, Marlina hanya beberapa kali menjenguk. Setiap bertemu, suaminya selalu menanyakan anak-anak.
“Dia cuma bilang, jaga anak-anak. Itu saja. Jangan sampai putus sekolah,” tuturnya.
Kalimat itu yang terus terngiang di kepalanya.
Di sela meraut lidi, Marlina berhenti sejenak. Mengusap mata dengan ujung kerudung. Ia tak bicara tentang keadilan atau pasal hukum. Itu urusan aparat dan pengadilan.
Yang ia pikirkan sederhana bagaimana besok tetap ada nasi di piring, bagaimana anaknya bisa sembuh, bagaimana mereka bisa tetap sekolah.
“Saya cuma mau anak-anak sehat. Jangan sampai masa depan mereka ikut hancur,” katanya lirih.
Di sudut rumah, tumpukan lidi yang sudah diraut mulai menggunung. Ia mengikatnya pelan-pelan, satu per satu. Seperti mengikat kembali sisa-sisa hidup yang tercerai.
Di tengah dua luka, anak yang menjadi korban dan suami yang dipenjara, Marlina memilih bertahan. Bukan karena kuat, tapi karena tidak punya pilihan lain.