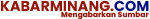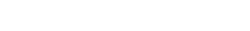“Uang itu untuk semuanya. Untuk makan, untuk keperluan istri,” kata Yusak.
Namun, jumlah itu sering kali tak cukup. Untuk makan sehari-hari saja pas-pasan. Untuk berobat, hampir mustahil. Air bersih sepenuhnya bergantung pada hujan. Saat kemarau panjang datang, mereka hanya bisa menunggu dan berhemat pada rasa lapar.
Rumah itu bukan sekadar bangunan reyot. Ia merupakan potret keterbatasan dari berbagai sisi: ekonomi yang rapuh, kesehatan yang terabaikan, usia yang menua tanpa jaminan, dan masa depan yang tak jelas arahnya.
“Kadang-kadang saya takut memikirkan besok. Saya sudah tua. Istri sakit. Anak tidak bisa apa-apa. Kalau saya tidak ada nanti, mereka bagaimana?” tutur Yusak.
Pertanyaan itu tak membutuhkan jawaban. Ia menggantung di udara, bersama sunyi rumah kayu yang nyaris runtuh.
Kisah keluarga Yusak bukan tentang angka kemiskinan dalam laporan statistik. Ia bukan grafik, bukan persentase. Ia kisah yang hidup diam-diam, jauh dari sorotan: tak gaduh, tak dramatis, tetapi nyata.
Hari-hari mereka diisi dengan kecemasan sederhana: bagaimana bertahan hidup hari ini, besok makan apa. Meski demikain, Yusak tak pernah benar-benar putus asa. Secara mental, ia menyerahkan hidupnya kepada Yang Maha Kuasa. Dalam tubuh ringkihnya, ia terus berusaha berdiri.
“Sujud dalam salat lima waktu cukup juga sebagai pengganjal saat perut lapar,” katanya lirih.
Doanya sederhana: semoga suatu hari nanti tangan-tangan baik datang membawa harapan meski hanya cukup untuk bertahan hidup.
Di rumah kayu yang pelan-pelan dilupakan dunia itu, kemiskinan tak berteriak. Ia tinggal, menetap, dan menua bersama penghuninya.